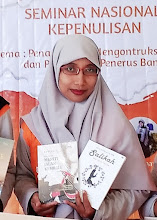Sekolah merupakan tempat interaksi manusia yang memungkinkan munculnya perilaku produktif atau kontra-produktif dalam upaya pencapaian tujuan lembaga, pemenuhan terhadap tuntutan dan kepuasan pemangku kepentingan pendidikan (stakeholders), dan efektifitas serta efisiensi penggunaan sumber daya dari masyarakat dan negara. Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan sekolah harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan stakeholders (peserta didik, orang tua, masyarakat umum, pemerintah, dunia usaha dan dunia industri), baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sehingga diharapkan dapat memunculkan partisipasi dan mitra yang positif dari masyarakat terhadap sekolah.
Dengan demikian, keterlibatan stakeholders pendidikan dalam membina dan membantu menyelenggarakan sekolah merupakan bagian dari penyelenggaran good governance pada lembaga pendidikan. Hudson (2007) mengemukakan dalam artikelnya yang berjudul
“Governing the Governance of Education: the state strikes back? Temuan Hudson menunjukkan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan babak baru yang diharapkan dapat meningkatkan mutu, efektifitas, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, tata kelola sekolah diduga masih belum banyak pelaksanaan dengan berpegang pada prinsip good governance. Pelaksanaan good governance dalam tulisan ini ditinjau berdasarkan Sembilan karakteristik good governance yang dikemukakan oleh UNDP, yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Tulisan ini berdasarkan hasil penelitian penulis di sejumlah SMAN di Kota Surabaya. Responden penelitian adalah kepala sekolah, para guru, staf tata usaha, siswa, pengurus komite sekolah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen, untuk menjawab empat pertanyaan berikut: Pertama, Bagaimana pelaksanaan good governance di SMAN Kota Surabaya?Kedua, Peran apa yang dilakukan personil sekolah dalam pelaksanaan good governance? Ketiga, Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan good governance di sekolah?dan Keempat, Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan good governance di sekolah?
Temuan penelitian ini secara singkat diuraikan sebagai berikut:
Partisipasi Masyarakat, Implementasi partisipasi masyarakat di SMAN Kota Surabaya secara formal diwadahi melalui komite sekolah. Implementasi peran komite sekolah tidak saja sebagai penampung aspirasi, tetapi benar-benar menjadi mediator bagi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah.
Namun demikian dalam pelaksanaannya, belum semua unsur yang berkepentingan dengan sekolah berkontribusi dengan baik terhadap penyelenggaraan sekolah.
Tegaknya Supremasi Hukum, Penegakan supremasi hukum di SMAN Kota Surabaya dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh warga sekolah (kepala sekolah, guru-guru, staf sekolah, komite sekolah, dan siswa), dan kepala sekolah telah melaksanakan berbagai bentuk supremasi hukum dalam manajemen kelembagaan sekolah.
Hal ini dirasakan memuaskan oleh para staf dan guru, termasuk oleh siswa. Namun demikian, ada hal yang menjadi catatan dalam penegakan supremasi hukum ini berdasarkan pengamatan selama penelitian, yaitu: Pertama, Tidak ada slogan-slogan pemberitahuan di sekitar lingkungan sekolah; Kedua, menurut beberapa informasi adanya kekurang-sadaran guru untuk mengisi daftar hadir (absensi) dan sering harus selalu diingatkan oleh piket.
Transparansi, Pelaksanaan transparansi di SMAN Kota Surabaya tidak luput dari peran kepala sekolah dalam melakukan manajemen sekolah. Dukungan dan tuntutan transparansi muncul dari stakeholder dan guru beserta staf sekolah. Salah satu bentuk transparansi dilakukan melalui brefing hari senin (rutin setiap hari senin, pukul 07.15-07.45) dalam upacara bendera, dimana segala informasi dan keluhan dapat disampaikan pada saat brefing berlangsung, menjadi media komunikasi antara pihak sekolah dengan siswa. Dengan begitu Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tidak hanya diketahui oleh pihak sekolah, tetapi juga menjadi pegangan bagi para pengurus sekolah. Dalam proses pembuatannya, RKAS dikembangkan bersama antara pihak sekolah dengan komite sekolah.
Peduli pada Stakeholder, Pelaksanaan “peduli terhadap stakeholder” dapat dilihat pada tiga bentuk Layanan yaitu: Layanan terhadap siswa, Layanan terhadap orang tua, Layanan terhadap masyarakat. Orientasi layanan terhadap stakeholder menjadi salah satu orientasi dari kerja personil sekolah. Namun demikian, orientasi ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak, apabila dilihat dari kondisi fisik lingkungan sekolah (kaca-kaca kelas, meja, kursi) yang masih kotor selama proses belajar mengajar berlangsung.
Berorientasi pada Konsensus, Pembuatan kesepakatan-kesepakatan antara kepala sekolah dengan guru dan staf sekolah merupakan bagian dari perilaku yang sudah biasa dilakukan. Media untuk membuat berbagai kesepakatan adalah brefing hari senin setelah Upacara Bendera. Berbagai kesepakatan pihak sekolah juga dilakukan dengan pihak stakeholder sekolah, baik secara langsung maupun melalui komite sekolah. Rapat rutin pihak sekolah dengan komite sekolah dilakukan minimal selama dua kali dalam setahun, kecuali apabila terjadi kondisi yang emergensi, seperti ketika sekolah diberikan tawaran untuk menjadi sekolah unggulan, maka kepala sekolah secara langsung mengundang pengurus komite sekolah untuk mendiskusikannya.
Kesetaraan, Kesetaraan berlaku dalam proses interaksi keseharian diantara warga sekolah. Demikian halnya perlakuan pimpinan sekolah terhadap warga minoritas. Hal ini dapat dilihat dari upaya sekolah untuk membujuk siswa yang berhenti sekolah, yang didasarkan pada ketidakmampuan orang tua membiayai putera/puterinya bersekolah sehingga siswa tersebut kembali ke sekolah. Hal ini pun terjadi pada perlakukan terhadap guru honorer. Guru honorer diperlakukan sama dengan guru yang sudah menjadi PNS, termasuk dalam peningkatan kesejahateraannya. Kebijakan sekolah dan implementasinya tidak membeda-bedakan antara orang di dalam sekolah, bahkan didorong untuk terus memiliki kinerja yang lebih baik.
Efektifitas dan Efisiensi, Efektifitas dan efisiensi dilihat dari tingkat kelulusan siswa, tahun 2019/2020 pada saat pandemi covid 19 dilakukan secara online dan dinyatakan lulus 100%. Dilihat dari serapan yang diterima di Perguruan Tinggi rata-rata 47%, sedangkan 53% diterima di dunia kerja (tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi). Dilihat dari prestasi non akademik, siswa-siswa banyak mendapatkan juara I baik pada level kabupaten, provinsi, maupun nasional dan internasional. Kinerja guru, kepala sekolah secara langsung mengamati dan membina penampilan guru di kelas dan dilakukan untuk semua guru.
Akuntabilitas, Semua dana bantuan dari Pemerintah yaitu BOS dan BPOPP, penggunaannya dilakukan secara akuntabel kepada pihak pemberi dana. Akuntabilitas program dilakukan melalui pelaporan program, bahkan pengecekan hasil program. Pemahaman akuntabilitas terbatas pada pemberi dana atau pemberi program, sedangkan akuntabilitas terhadap siswa dan orang tua masih jarang dilakukan. Mediasi melalui buku catatan belum menjadi mediator kepada orang tua untuk memberikan informasi mengenai perkembangan anaknya.
Visi Strategis, Sekolah menyadari akan pentingnya Visi dan Misi Sekolah. Dalam pelaksanaannya, belum semua warga sekolah memahami dan mampu menjabarkannya dalam bentuk perilaku. Yang terjadi adalah warga sekolah memiliki keyakinan terhadap keberhasilan yang akan dicapai oleh sekolah. Permasalahan yang sering dialami oleh warga sekolah adalah belum semua warga sekolah memahami visi dan misi sekolah, mengapa visi dan misi itu ada, dan apa pentingnya peran dia dalam pencapaian visi dan misi sekolah. Hal ini teridentifikasi disebabkan beberapa oleh dua hal: Pertama, ada personil sekolah yang kurang berminat untuk membahas dan membicarakan hal-hal seperti ini. Bagi dirinya, yang penting adalah melaksanakan tugas. Kedua, dalam proses penyusunan dan pengembangan visi sekolah ke depan yang tertuang dalam RKAS tidak secara penuh melibatkan semua dalam pembahasannya.
Dari Sembilan karakteristik good governance yang terlaksana di sekolah, ada dua karakter yang patut diberi catatan, yaitu: akuntabilitas dan visi strategis. Kedua karakter ini dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang terbatas, yakni mempersepsi akuntabilitas penggunaan dana atau pelaksanaan program dilakukan setelah kegiatan selesai dan dilakukan kepada orang/pihak yang memberi dana/kuasa, karena ada tuntutan akan hal tersebut. Dalam pandangan The Liang Gie dkk (2002:4), akuntabilitas lebih mengarah pada proses pangilan jiwa yang merupakan suatu kebutuhan dari diri sendiri untuk mendapat umpan balik dari stakeholdernya atau pemberi pekerjaan. Dapat dikatakan, akuntabilitas kerja masih dalam tataran wacana, belum sampai pada asumsi dan perilaku yang menetap. Jika ada dasar dari akuntabilitas adalah tuntutan juklak juknis, bukan sebagai kebutuhan professional. Kebanyakan guru masih menganggap tugasnya adalah mengajar. Setelah mereka mengajar maka mereka bebas dari tugas. Walaupun dalam perspektif yang lebih jauh, guru harus mampu menjawab pertanyaan “untuk apa mereka mengajar?” pertanyaan itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh semua personil sekolah harus mengarah pada satu tujuan bersama. Mengkomunikasikan visi dan menjadikannya sebagai kepemilikan semua warga organisasi bukan suatu pekerjaan mudah karena terkait dengan karakter perilaku orang di dalam organisasi yang memiliki keunikan. Sebagian orang memiliki pemahaman yang generalis, yang lain memiliki pemahaman yang spesifik.
Coulson-Thomas (1992, dalam Salusu, 1996:131) mengakui bahwa mengkomunikasikan visi ke seluruh tubuh organisasi tidak semudah digambarkan dalam teori. Perumusan visi strategis adalah tanggungjawab dari manajemen puncak. Namun, hal itu merupakan proses interaksi yang memberi peluang untuk mendapatkan umpan balik dari semua unsur organsasL (Salusu, 1996:129).
Peran-peran personil yang beragam di sekolah menunjukkan adanya pembagian kerja berdasarkan karakteristik jabatannya di sekolah. Hal ini seiring dengan yang dikemukakan Harrison (2001) yang memandang profesional (SDM) organisasi-lah yang akan membawa perubahan atau kehancuran organisasi. Maju mundurnya organisasi tergantung pada kemampuan orang dalam organisasi melakukan pekerjaannya. Keengganan personil sekolah untuk melakukan suatu perubahan terkait dengan peran yang harus dilakukannya disebabkan karena beberapa faktor, (1) kepemimpinan yang tidak cukup kuat, (2) salah melihat reformasi (perubahan), (3) sabotase di tengah jalan, (4) komunikasi yang tidak begitu bagus, (5) masyarakat yang tidak cukup mendukung, (6) proses “buy-in” tidak berjalan. (Kasaft, 2005:12-13).
Tidak terlaksananya good governance secara lengkap menunjukkan masih kurang pemahaman akan tujuan dari good governance. Bukan saja pengetahuan, tetapi pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hal tersebut dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah belum mencukupi.
Dengan demikian, tidak hanya guru yang memiliki peran penting dalam good governance tetapi semua unsur, yakni: sekolah, masyarakat, orang tua, dan pemerintah memiliki peran yang penting untuk keberhasilan good governance.
Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah struktur organisasi, delapan nilai kerja yang dikembangkan sekolah, sikap warga sekolah dalam menjaga lingkugan fisik, dan hubungan baik dengan stakeholder. Sedangkan faktor penghambat adalah berkisar pada hal-hal: fasilitas fisik sekolah yang sedang dalam pembangunan, budaya kerja individu yang kurang baik, rendahnya motivasi kerja, dan kurangnya kesadaran guru dalam pengembangan sekolah. Pelaksanaan good governance dapat dikatakan sebagai suatu inovasi (hal yang baru).
Kjell Skogen (1997) mengemukakan ada beberapa hal yang dapat menghambat tumbuhnya inovasi, yaitu: faktor psikologis, praktis, dan nilai serta kekuasaan. Faktor-faktor psikologis adalah: rasa bersalah, kebutuhan akan pengakuan, keinginan untuk menguasai, pola peranan yang kaku dalam sistem sosial, pola perilaku yang kurang pertimbangan, atau ketidaktahuan tentang masalah. Hambatan praktis yang dihadapi adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik, yaitu: waktu, sumber daya, dan sistem.
Berdasarkan analisis dari Skogen, hambatan yang terjadi ada pada faktor psikologis dan praktis. Secara psikis, warga sekolah masih belum sadar akan pola perilaku yang kurang pertimbangan atau tidak pantas yang dipertahankan berdasarkan prinsip-prinsip imbalan tertentu, atau ketidaktahuan tentang masalah. Secara fisik, sekolah masih harus ditata, dikembangkan, dan direnovasi.
Yang terjadi saat ini, dominasi peran komite sekolah masih pada bantuan/dukungan dana untuk berbagai kebutuhan penyelenggaraan sekolah walau sejatinya masyarakat memiliki berbagai sumber daya, bahkan mungkin sumber daya yang tidak terbatas untuk penyelenggaraan sekolah yang lebih baik. (Hoy & Miskel: 2001).
Mahasiswa Magister Ilmu Politik,
Fakultas FISIP Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya

.png)